Jam
lima lewat lima belas, masih setengah jam lagi, bisikku dalam hati yang baru
saja menelisik jam analog yang melingkar di lengan kiriku. Sudah lama juga
rupanya aku di sini. Benar kata orang jika waktu akan bergerak begitu cepat
bila kita terlalu menikmatinya. Seperti aku saat ini. Aku terlalu menikmati
waktu yang kuhabiskan bersenda gurau bersama teman-teman semasa SMA-ku. Duduk
bersama di satu meja, bernostalgia dengan ketololan-ketololan dulu, tergelak
sesukanya seolah menertawai kebodohan-kebodohan kita dulu. Ya, kita─aku dan kamu.
Aku harap kamu akan datang di acara reuni kecil ini yang selalu ada hampir di
setiap tahunnya, saat bulan ramadan menyapa. Ya, aku masih menunggumu.
Apa
kamu masih ingat denganku, Fan? Ah, pertanyaan yang bodoh. Aku yakin kamu masih
sangat ingat denganku kecuali jika mendadak kamu terserang alzheimer, karena baru kemarin kita bertatap muka melalui Skype. Tapi, bukan itu maksud
pertanyaanku. Maksudku, apa kamu masih ingat dengan semua waktu yang pernah
kita habiskan bersama semasa SMA dulu? Ya, kita─aku dan kamu.
Ah,
sial! Kata-kata itu selalu melekat di benakku. Apa kata-kata kita itu cocok untuk menggambarkan kita yang sekarang ini? Kita yang masih menjaga tali silaturahim
walau jarak tetap memisahkan kita di
antara dua negara yang berbeda. Aku di negara kelahiranku, Indonesia, sedangkan
kamu di negara kelahiran Kanguru, Australia. Tapi, kurasa kita yang sekarang ini masih kita
yang dulu, dan tak ‘kan pernah menjadi kita
dalam arti sebenarnya. Ah, sudahlah. Sepertinya terlalu banyak kata kita dapat membuat kepalaku jadi pusing
sebelah.
“Dera.
Gue denger-denger Fani udah pulang dari Australia?” temanku Doni bertanya
padaku. Wajahnya nampak semringah saat mendengar kabar burung yang entah dari
mana ia terima.
“Katanya,
sih,” jawabku datar.
“Gue
denger-denger lo masih sering komunikasi sama dia, ya?” tanyanya lagi yang kini
makin melekatkan pandangannya ke arahku.
Aku
mengernyitkan keningku. Mengapa orang ini bisa banyak mendengar kabar yang
bahkan aku sendiri belum pernah mengatakannya kepada siapapun? Apa dia ini
cenayang, atau semacam anak indigo yang dapat berkomunikasi dengan makhluk
halus sehingga dia banyak mendengar kabar angin?
“Iya.
Masih, tapi cuma gitu-gitu aja,” jawabku dengan nada yang masih sama.
“Eh-eh.
Gue denger-denger dia sekarang udah banyak berubah, ya, Der?” sahut Andien.
“Iya.
Katanya sekarang dia makin modis gitu.” Riani tak mau ketinggalan.
Semakin
lama gosip tentangmu pun merembet di antara kami. Mereka semakin asik
membicarakanmu yang selalu diawali dengan kalimat katanya dan gue
denger-denger. Kamu tahu apa yang kulakukan saat ini? Aku hanya duduk diam
sembari sesekali menggaruk-garuk kepalaku saat mendengarkan mereka yang terus
saja menggosip tentangmu. Membuatku berharap agar kamu cepat datang!
Sekali
lagi kumenelisik jam analog di lengan kiriku. Sepuluh menit lagi sudah waktunya
untuk berbuka puasa, tapi batang hidungmu saja belum kulihat hingga detik ini.
Aku mengambil ponselku dan membuka pesan yang baru saja kukirimkan padamu. Dahiku
mengerut. Pesan itu benar sudah terkirim sekitar lima belas menit yang lalu. Aku
menimbang-nimbang sejenak. Mencoba berpikir untuk menelponmu atau tidak. Tapi,
pada akhirnya aku pun segera menelponmu.
Sudah
dua kali aku mencoba menghubungimu tapi tak ada jawaban darimu. Sudah kubilang
untuk kujemput, tapi kamu malah menolaknya. Awas saja kalau sampai tak datang!
Aku menggerutu dalam hati. Menaruh kesal padamu! Tapi, baru saja aku menaruh
kembali ponselku di saku celanaku, tiba-tiba saja Riani memekik.
“Faniii!!!”
Riani memekik hingga membuat semua orang di dalam tempat makan ini menengok ke
arahmu. Ya, ke arahmu yang baru saja datang dan langsung disambut oleh pelukan
Riani. Teman yang sangat dekat denganmu dulu.
“Ya,
ampun, Fani. Lo sekarang udah bener-bener beda, ya!” Riani berseru takjub.
“Iya,
lho! Makin semok!” sahut Diana yang ikut menghampirimu. Mereka, teman-teman
perempuan menghampirimu dan memberikan ribuan pujian padamu. Sedangkan
teman-teman pria hanya duduk seraya mengagumi perubahanmu. Mata mereka menyorot
padamu. Nampak berbinar-binar, seperti bayi yang melihat sebotol susu
dihadapannya ketika sudah sangat lapar. Sementara aku, hanya duduk di tempaku
berada, tak beranjak sedikit pun seraya memandangi pipimu yang memerah. Aku
tahu pipimu memerah karena banyaknya pujian yang mereka limpahkan padamu, dan
kamu hanya tersenyum sipu menanggapi itu. Kamu hanya tersenyum, sama sepertiku
yang saat ini sedang tersenyum kepadamu, memandangimu. Akhirnya, aku bisa
kembali melihat wujud aslimu, tanpa harus menatap wajahmu lagi melalui layar
laptopku.
Sekali
lagi, waktu seakan bergerak cepat ketika kita terlalu menikmatinya. Sudah jam
delapan malam, dan kita masih asik bernostalgia di sini. Di sebuah tempat makan
yang beratapkan kaca hingga kita bisa melihat bintang di atas sana dengan
jelas. Walau kenyataannya langit Jakarta malam ini sedang tak berbintang. Bila
berbicara soal bintang aku selalu teringat padamu. Ya, padamu yang selalu suka
dengan bintang.
Kamu selalu
percaya kalau bintang itu adalah perwujudan dari orang baik yang telah
meninggal. Tuhan sengaja menempatkan mereka di atas sana dengan sinar yang
terang, agar mereka bisa terus melihat orang terkasih dari tempat mereka berada
sekarang. Dan kamu selalu menunjuk ke arah satu bintang. Satu bintang yang sama.
Dan dengan suara lirihmu, kamu selalu mengatakan bila itu adalah bintang Ibumu.
Ya, Ibumu yang telah lama pergi sejak kamu masih kecil dulu. Kamu selalu
percaya jika itu adalah bintang Ibu karena bintang itu selalu berbinar ketika
kamu sedang bahagia, dan bintang itu akan redup seketika bila kamu sedang
dilanda duka.
Sadarkah kamu
bila sejak tadi kita selalu saling mencuri pandang lalu tersenyum setelahnya. Dan
seakan tersadar jika itu terlarang, kita akan saling melempar pandangan ke
tempat lain. Melemparkan deru jantung yang memburu ini ke objek yang lain. Ya,
lagi-lagi kita─aku dan kamu. Apa kamu akan mengingkari itu, Fani? Tak masalah
memang jika kamu mengingkari itu pada siapapun saat ini karena kita memang
selalu menyembunyika kedekatan yang ada ini, bukan?
Aku selalu
senang bisa dekat denganmu walau harus disembunyikan sekalipun. Aku tak pernah
tahu apa alasanmu tak ingin semua orang tahu kedekatan kita. Entahlah, tapi aku
tak pernah terlalu ingin tahu soal itu. Karena tak semua hal selalu baik untuk
terlalu dalam kita ketahui. Aku juga selalu suka tiap kali kamu tersenyum. Aku
suka saat sudut bibirmu yang tipis itu melengkung naik, membuat sebuah lekukan
seperti sebuah lubang di pipimu terlihat jelas. Itu lesung pipitmu. Tapi, apa
kamu tahu bila ada hal yang kubenci darimu? Kuberitahu, aku begitu membencimu
bila kamu memberikan senyummu itu kepada lelaki lain, atau saat kamu memberikan
sorot matamu yang bulat itu kepada pria lain. Ya, aku benci hal itu!
“Kamu sekarang
lagi sibuk apa Fan?” tanya Biondi yang duduk tepat berhadapan denganmu.
“Aku sekarang
lagi sibuk nyiapin wisuda aku aja, sih,” jawabmu seraya menyelipkan beberapa
helai rambutmu ke belakang telingamu. Sebuah gerakan sederhana yang membuatku
terpana. Dari sini, aku bisa melihat jelas wajahmu. Dan juga lesung pipitmu.
“Oh, ya? Udah
lulus dong. Terus rencananya mau tinggal di sini atau di Australia?”
“Rencana sih mau
mencoba berkarir dulu di sini. Mau bekerja untuk tanah air sendiri dulu, yon.”
“Wih, hebat juga
ya.”
Kamu
mengernyitkan keningmu. “Hebat? Apanya?”
“Ya, kamu sudah
lulus dari luar negeri tapi masih mau mencoba bekerja untuk negaramu sendiri.”
“Nggak salah
dong mengabdi untuk negeri. Ya, kan?” ujarmu yang terkekeh.
Perbincanganmu
dengan Biondi terus berlanjut. Dan entah kamu sadari atau tidak, kamu telah
banyak memberikan senyum manismu itu kepadanya. Matamu yang bulat itu juga
selalu menatapnya penuh minat. Entahlah, tapi percakapan kalian telah membuatku
sedikit resah. Apalagi kalau harus berhubungan dengan Biondi. Pria itu bisa
dibilang sebagai idolanya perempuan di SMA dulu., walau kutahu kamu tak pernah
sedikit pun berniat menjadi kekasihnya. Tapi, penampilannya saat ini membuatnya
mudah untuk menaklukan hati perepuan manapun. Tubuhnya lebih tegap, lebih berisi.
Lengannya berotot, namun tak berlebihan. Rambut cepaknya dan wajahnya yang
belasteran Indo-Arab itu benar-benar membuatku gundah. Sebenarnya yang
membuatku gundah adalah kedekatanmu dengannya tadi. Apa kini kamu mulai
tertarik dengannya?
Dari tempatku
duduk yang berada di barisan Biondi, hanya terpaut tiga kursi darinya, aku
masih memerhatikan semua gerak tubuhmu. Sesekali kamu tersenyum sipu, sesekali
kamu terkekeh bersamanya, sesekali kamu nampak begitu memerhatikannya bercerita.
Kamu tahu, itu benar-benar membuatku bergelut dengan keresahanku sendiri. Ada
yang menggelegak di nadiku seolah aku akan meledak, tapi di saat yang bersamaan
seperti ada yang menyayat pelan arteriku seolah aku ingin mati. Sulit memang
untuk aku deskripsikan bagaimana kalutnya aku saat ini. Tapi, bagaimanapun aku
tak ingin orang lain tahu keresahanku padamu. Aku tak ingin mereka tahu jika
ada yang terpendam di dada ini untukmu. Aku tak ingin mereka tahu, termasuk
kamu.
***
Dari
tempatku berdiri saat ini, aku melihatmu melambai ke arahku. Tubuhmu yang tak
terlalu tinggi membuatmu harus berjinjit seraya melambaikan senyummu ke arahku.
Kamu berteriak memanggil namaku di tengah ramainya orang-orang di Stasiun Senen
siang ini. Aku melambai kepadamu sebelum akhirnya aku berlari menghampirimu.
“Kok,
lama banget sih?” tanyamu.
“Sori.
Tahu sendirikan gimana macetnya Jakarta.”
Hari
ini kita bertemu di Stasiun Senen, sesuai dengan rencana kita seminggu yang
lalu. Saat itu kamu memintaku untuk menemanimu berlibur di Jogja. Aku yang
masih sibuk dengan pekerjaanku tak bisa langsung menyanggupi permintaanmu,
namun kamu terus memaksaku. Bahkan kamu memohon kepadaku seraya menatapku
dengan tatapan manja melasmu. Mata bulatmu menatap melas ke arahku? Ya, kamu
benar-benar tahu bagaimana membuatku luluh. Saat itu kamu berseru riang ketika
akhirnya aku menyerah dan menerima permintaanmu. Aku meninggalkan pekerjaanku
yang menumpuk di meja kerjaku. Aku meminta cuti kepada atasanku. Tak begitu
sulit memang untuk meminta cuti kepada atasanku karena ia sangat memercayaiku.
Dan kemudahan itulah yang memang selalu kamu manfaatkan untuk mengajakku
menemanimu berlibur.
“Kamu
udah makan?” tanyamu dengan mata yang selalu kusuka.
Aku
menggeleng.
Kamu
melirik jam tangan analog yang melingkar di lengan kananmu. “Masih satu jam
lagi,” ujarmu. “Kita makan soto dulu, yuk!”
Tanpa
berpikir panjang aku langsung mengiyakannya. Kita segera melangkahkan kaki
menuju salah satu penjual soto ayam yang kiosnya berada di dekat pintu keluar
penumpang kereta api. Di sana kita berdua duduk di atas kursi plastik berwarna
hijau tanpa sandaran lengan. Kita duduk bersama tepat di depan gerobak soto
ayamnya. Kamu memesan soto ayam seraya mengacungkan dua jarimu kepada
penjualnya. Hal yang sama juga kamu lakukan ketika memesan minum.
“Kalau
sudah sampai di Jogja kita mau nginep di mana?” tanyaku seraya melepaskan
jaketku.
“Nanti
kita nginep di rumah temen aku aja. Kebetulan aku punya kenalan di sana,”
jawabmu yang selalu murah senyum. “Tenang aja, pokoknya liburan kita kali ini
irit kok,” serumu yang lagi-lagi tersenyum riang.
Kamu tahu bila
aku sangat membencimu ketika kamu selalu memerlihatkan senyummu itu padaku? Ya,
aku benci hal itu karena tindakanmu itu selalu membuatku mudah merindukanmu.
Jam
tiga sore, dan kita sudah berada di dalam kereta api ekonomi Progo. Kamu duduk
di dekat jendela dan aku duduk di dekatmu. Aku tahu kamu selalu suka melihat
bintang, makanya aku sengaja menyuruhmu duduk di dekat jendela. Sesaat kemudian
kereta mulai bergerak. Perlahan tapi pasti suara roda besi yang bergesek dengan
permukaan rel terdengar menderu. Kini kita sudah bergerak menuju Jogja.
Tak
ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut kita dari awal keberangkatan hingga
kereta ini melewati Stasiun Cirebon Prujakan. Sejak tadi kamu hanya termenung
sambil menatapi pemandangan luar dari kaca jendela. Kamu melihat barisan pohon
yang seolah berlari menghampiri kita. Wajahmu hanya menyudut membelakangiku.
Entahlah, aku tak tahu mengapa kamu sehening ini. Tak biasanya selama
perjalanan kamu semurung ini. Apa karena kali ini kamu menuruti keinginanku
yang hanya mau naik kereta ekonomi? Tapi, kalau memang suasana kereta ekonomi
tak begitu menyenangkan untukmu, menagapa tak kau katakan saja kepadaku? Aku
tak keberatan bila harus sedikit merogoh uang tabunganku hanya untuk
menyenangkanmu. Ya, hanya untukmu.
Kini
kereta api kita sudah melewati Stasiun Purwokerto. Sesaat aku mendengar helaan
napas yang panjang tepat di sebelahku. Helaan napas yang panjang sebelum
akhirnya kamu mengalihkan wajahmu dan perlahan menyandarkannya di bahuku. Aku
tersentak sesaat. Di tengah kantuk yang menggelayuti mataku, tiba-tiba saja
kamu menyandarkan kepalamu di bahuku, membuat kantukku sirna dalam sesaat.
Sejenak kamu membenarkan dudukmu yang tak nyaman itu. Kamu menggeser pinggulmu
sehingga membuat tubuhmu kini melekat padaku. Desir darahku seolah terjun bebas
menelusuri arteriku. Perlahan kamu melingkarkan tanganmu di tangan kananku,
membuat jantungku menderu kencang seolah akan mencelus dari mulutku. Kamu
semakin merekatkan tubuhmu kepadaku, membuatku merasa serba salah untuk
bergerak. Untuk sesaat aku layaknya sebuah manekin.
“Dera.
Aku bolehkan bersandar seperti ini di bahu kamu?” tanyamu dengan suara lirih.
Aku
menarik napasku panjang. Saat ini aku tak berharap kamu akan mendengar degup
jantungku yang memburu ini. “Kenapa aku harus melarang kamu,” jawabku yang saat
itu penuh kehati-hatian.
“Makasih,
Dera,” ujarmu yang kemudian disambung dengan keheningan yang cukup lama.
Entahlah mengapa kamu bisa sehening itu saat sudah menyandarkan kepalamu di
bahuku. Apakah karena kamu nyaman di sana atau memang kamu hanya sedang
melarikan kerinduanmu padaku? Hanya kamu yang tahu saat itu.
Harus
kuakui, Fan. Saat kau membisu seperti ini aku merasakan kehambaran seketika.
Sudah lebih dari enam tahun kita saling mengenal dan aku masih tak tahu harus
melakukan apa untuk bisa membuatmu, setidaknya berbicara untuk saat ini.
Mungkin sebagai lelaki aku memang lelaki yang bodoh karena aku tak bisa membuat
suasana hatimu yang mungkin saat ini sedang redup untuk kembali benderang.
Tapi, harus kuakui juga, bila saat ini aku begitu menikmati kedekatan kita,
Fan. Ya, kita─aku dan kamu. Begitu lama aku sudah tak merasakan kedekatan kita
seperti ini. Terakhir kita seperti, empat tahun yang lalu sebelum kamu
memutuskan berkuliah di negeri Kanguru itu.
Lagi-lagi
kembali muncul kata-kata “Kita”. Entah mengapa kata-kata itu selalu
menggangguku. Selalu menghantuiku. Aku tak tahu bagaimana denganmu. Apa kamu
pernah memikirkan tentang pengartian kata kita
untuk kita saat ini, Fan?
***
Udara
pagi di Jogja memang lebih menyegarkan jika dibandingkan Jakarta. Pagi ini, di
halaman rumah temanmu, kita menikmati udara pagi bersama. Udara yang sejuk,
dingin, dan menyegarkan. Kita merentangkan kedua tangan kita, menarik napas
begitu dalam, membiarkan udara pagi Jogja memenuhi paru-paru kita, sebelum
akhirnya kita kembali mengembuskannya. Sehabis melakukan itu, entah mengapa
kita tertawa bersama. Maksudku, kita saling menertawakan. Kita saling
menertawai karena saat kita mengirup udara tadi, tak sadar kita saling menatap.
Pipimu yang mengembung saat sedang mengirup udara membuatku tak tahan untuk
tergelak. Wajahmu sangat mirip dengan Sinchan. Sementara kamu tergelak
kepadaku, menertawaiku karena kamu bilang mataku nampak tenggelam di antara
pipiku. Membuatmu tergelak menahan sakit.
“Masih
pagi kok udah cekikikan aja. Awas kalau sampai tetanggaku ngomel, yo,” sahut Mariska sembari membawa dua
cangkir teh hangat dengan sebuah nampan.
“Nggak
apa-apalah Ris. Lagian katanya orang Jogja itu ramah-ramah. Masa ketawa gini
aja dimarahin sih,” ujarmu yang masih terduduk lemas di teras rumahnya. Sebelah
tanganmu memegangi perutmu yang terasa keram karena gelakmu yang berlebihan. Rasakan
itu karena kamu menertawaiku!
“Ramah
sih ramah. Tapi, kalau sudah keganggu, ya bisa galak juga, Fan,” ujar Mariska
dengan logat jawanya yang halus. “Diminum dulu nih tehnya sebelum dingin. Aku
mau bantu Ibu masak dulu di dapur, yo.”
Kita
mengangguk bersamaan seraya tersenyum kepadanya. Mariska kemudian menghilang
dari balik pintu meninggalkan dua cangkir teh hangat di atas meja kayu bulat
yang kecil itu.
“Kamu
nggak ikut ngebantuin Mariska sama ibunya masak, Fan?” tanyaku seraya
melangkahkan kaki menuju teras.
Wajahmu
tiba-tiba saja menekuk. “Kamu kan tahu aku paling nggak bisa masak.”
“Oh,
iya. Waktu di Australi aja kamu punya tukang masak sendiri, ya.”
Kamu
mengangguk padaku. Tapi, masih dengan wajah yang menekuk.
Aku
duduk di kursi kayu berwarna cokelat dengan sandaran lengan itu. Aku mengambil
salah satu cangkir. Asap masih nampak mengepul dari cangkir yang sedang
kupegang ini, menandakan jika teh ini masih benar-benar panas. Aku mendekatkan
gelas itu ke mulutku. Segenggam udara kuhembuskan dari mulutku, mengangini
permukaan teh itu agar dapat cepat kutenggak. Setelah kurasa sudah tak lagi
panas, mulai kutempelkan bibirku ke pinggiran cangkir itu. Aku menyeruputnya
pelan, sedikit demi sedikit. Sesaat kemudian aku seperti baru merasakan sesuatu
yang enak.
“Sumpah
enak banget tehnya, Fan. Cobain deh!” seruku dengan perasaan yang entahlah,
mungkin bisa dibilang sedang berbunga-bunga.
Saat
itu kamu diam. Kamu hanya menatapku kelu dari tempatmu duduk saat ini. Ada yang
berbeda dari tatapan matamu. Entahlah, apakah kamu menyadarinya atau tidak.
Tapi, menurutku tatapan itu agak berbeda. Seperti sedang menghakimiku.
“Kamu
suka sama Mariska?” tukasmu datar. Ucapanmu membuatku tersedak hingga aku
terbatuk dibuatnya.
“Apaan,
sih, kamu,” sahutku yang masih terbatuk.
“Soalnya
muka kamu semringah banget waktu kamu minum teh buatan Mariska. Kayak anak
kecil baru ngerasain es krim. Aku juga tadi sempat ngeliat kamu curi-curi
pandang ke dia waktu dia nganterin tehnya. Ya, kan?”
Ucapanmu
berhasil membuatku menarik napas dalam-dalam. Sepertinya kamu sudah
memerhatikanku sejak tadi, ya. Kuakui jika aku memang sempat mencuri pandang ke
Mariska. Mungkin bukan ku saja. Tidak, tapi aku yakin pasti bukan aku saja yang
akan mencuri pandang padanya. Ia perempuan pemilik wajah yang manis dengan
senyum yang tak berlebih. Buatku semua yang dia miliki tak berlebih.
Benar-benar sesuai dengan takarannya. Hidungnya yang tak berlebih, tebal
bibirnya yang tak berlebih, putih kulitnya yang tak berlebih, dan juga suara
halusnya yang tak berlebih, ku rasa semua yang ada pada dirinya akan mampu
membuat semua pria sering-sering mencuri pandang padanya.
“Kenapa
memang kalau aku sampai suka sama dia? Kamu cemburu?” tukasku.
Air
mukamu seketika berubah. Tapi, belum sempat aku menelisik lebih jauh lagi, kamu
sudah mengalihkan wajahmu dari jarak pandangku. “Ngapain cemburu? Kamu kan tahu
aku sudah punya Bara,” sahutmu.
Ah,
nama itu lagi yang kamu sebut. Entah mengapa setiap kali mendengar nama itu ada
adrenalin yang memacu jantungku. Aliran darahku seolah menggelegak untuk keluar
dari nadiku. Ya, aku tahu kamu sudah memilikinya. Ia adalah lelaki hebat yang
berhasil menjatuhkanmu di pelukannya. Bahkan begitu hebatnya dia, pesan singkat
darinya bisa membuatmu kembali benderang dari redupmu di kereta semalam. Aku
tahu aku tak sehebat dia, dan kutahu aku tak pernah bisa sehebat dia.
***
Ada
yang menarik di Kota Jogja selain perempuannya yang sudah cantik secara alami,
yaitu suasana di alun-alun kidul Jogja saat malam menyapa. Saat itu Mariska
mengajak kita untuk pergi bersamanya. Menikmati suasana malam di alun-alun
jogja, begitu katanya dengan halus suaranya yang pas. Di sana kita menaiki
sebuah becak dengan kerangka yang sudah disambung dan dibentuk hingga
menyerupai bentuk angsa. Becak itu melekatkan lampu-lampu kecil berwarna violet
di sepanjang tubuh hingga paruhnya, dan warna merah di bagian matanya. Angsa
itu benar-benar menyala. Mungkin kalau di Jakarta becak ini bisa dibilang
odong-odong. Kita bertiga duduk di dalamnya, bersenda gurau bersama sambil
sesekali mengabadikan momen ini dengan berfoto bersama.
Malam
itu kita habiskan dengan tawa. Kita berjalan bersama. Ah, bukan, tapi
beriringan. Ya, karena kamu selalu melingkarkan tanganmu di lenganku. Kamu tahu
bila saat ini aku merasa telah menjadi kekasihmu? Apa aku berlebihan bila aku
merasakan hal itu karena sikapmu padaku. Kamu tertawa bersamaku, menggamit
lenganku erat, berbagi satu es krim bersama saat masih di alun-alun, kamu menyeka
noda makanan di sekitar mulutku saat kita selesai makan di angkringan. Aku rasa
aku tak berlebihan soal itu.
Malam
pertama kita di Jogja terbilang panjang. Kita masih melanjutkan petualangan
malam kita ketika di rumah Mariska. Di sana, di teras rumahnya. Kita duduk
bertiga di lantai sambil memandangi langit yang sedang cerah. Kamu memulai
perbincangan kita dengan membicarakan bintang-bintang. Malam ini kebetulan
langit Jogja sedang menampakkan tiga bintang yang berkelip di angkasa. Satu di
utara, dan dua lagi di timur.
“Dari
ketiga bintang ini, apa ada bintang ibumu, Fan?” tanyaku dengan kepala yang menengadah ke langit.
Kamu
menggeleng. “Nggak ada,” jawabmu memendam sedikit kekecewaan.
“Kamu
suka banget sama bintang, apa kamu percaya dengan ramalan bintang?” tanyaku
lagi. Kali ini aku menatap padamu.
Kamu
menggeleng lagi. “Nggak. Aku nggak pernah percaya.”
“Kalau
kamu, Ris. Apa kamu percaya?” tanyaku yang melempar pertanyaan.
Mariska
menggeleng. “Aku lebih percaya ramalan cuaca daripada ramalan bintang,”
jawabnya dengan aksen bicaranya yang polos, membuat kita berdua tergelak
mendengarnya.
Saat
kita berhenti tertawa kamu mulai bertanya, “Tapi aku penasaran, dari mana rasi
bintang-bintang itu ada?” keningmu mengerut.
“Itu
semua dari mitos Yunani,” jawabku mantap. “Semua rasi bintang yang dijadikan zodiak
itu punya mitosnya masing-masing.” Kamu mulai memerhatikanku dengan serius.
Begitu pun dengan Mariska. Matanya yang teduh itu memandangku penuh
keingintahuan.
“Bintang
kamu apa?” tanyaku padamu.
“Gemini,”
jawabmu cepat.
“Gemini,
ya?” aku mengingat sejenak. “Kalau nggak salah, gemini itu berasal dari dua
tokoh mitologi, yaitu si kembar Castor dan Pullox. Gemini itu terletak di
antara Taurus di barat dan Cancer yang redup di Timur,” jelasku seraya
menjulurkan tanganku ke angkasa. “Castor dan Pullox ini sedikit berbeda. Pullox
abadi sedangkan Castor tidak demikian. Sampai suatu ketika Castor meninggal
dalam sebuah peperangan. Pullox yang merasa tak bisa hidup tanpa saudara
kembarnya meminta kepada dewa Zeus, yang tak lain adalah ayahnya sendiri untuk mencabut
keabadian dari dirinya. Dengan begitu dia bisa bersama Castor selamanya. Tapi,
Zeus menolak. Zeus lebih baik membuat Pullox menjadi abadi dengan membuat
keduanya bersama selamanya sebagai kontelasi zodiak kembar. Merekalah Gemini
itu.”
“Berarti
Gemini itu bisa dibilang sebagai perwujudan kesetiaan, ya?” ujarmu
menyimpulkan.
“Bisa
dibilang begitu,” jawabku mengangguk. “Kalau bintang kamu apa, Ris?”
“Taurus,”
jawabnya yakin.
“Lho,
sama dong dengan Bara,” sahutmu yang tersentak. Kamu menyebut nama itu lagi.
Nama yang sebenarnya tak ingin kudengar. Sudah cukup rasanya mendengar nama itu
di setiap keluh kesahmu padaku. Nama itu selalu tersemat di ceritamu tiga tahun
terakhir.
“Taurus,
ya?” sahutku yang tak ingin lagi mendengarmu menyebut nama itu. “Kalau nggak
salah Taurus itu terletak di antara Aries di sebelah barat, dan Gemini di
sebelah timur. Taurus ini diidentifikasikan dengan Zeus yang berubah bentuk
menjadi banteng putih untuk menculik Putri Phoenicia yang bernama Europa.”
“Udah,
gitu aja?” serumu yang tak percaya.
“Iya.
Cuma itu yang aku ingat,” jawabku tanpa menoleh padamu. Sebenarnya aku masih
tahu soal mitologi Taurus itu, tapi aku sudah terlanjur malas karena aku tahu,
kamu akan menghubungkan ceritaku dengan lelaki itu.
“Kalau
bintang kamu apa, Dera?” tanya Mariska padaku. Matanya menelisik jauh ke dalam
mataku.
“Bintangku
Cancer. Cancer terletak di antara Gemini di sebelah barat, dan Leo di timur,” jelasku
yang langsung terdiam.
“Kok
diem?” tanyamu.
“Udah.
Itu aja,” jawabku.
“Masa
gitu? Curang nggak mau ngasih tahu lagi. Cerita lagi!” paksamu yang sudah
menarik-narik lengan bajuku.
“Udah.
Nggak ada lagi. Aku nggak tahu lagi,” jawabku sambil berusaha melepaskan lengan
bajuku dari cengkraman tanganmu.
Kamu
masih terus memaksaku, tapi aku terus menolak. Ya, aku menolak karena malas
menceritakan semuanya tentang rasi bintangku saat kutahu rasi bintang lelaki
itu adalah Taurus. Aku malas, Fan.
***
Satu
tahun sudah berlalu sejak terakhir kita pergi bersama. Ya, liburan kita ke
Jogja rupanya merupakan liburan terakhir kita. Karena setelah itu kamu lebih
sibuk dengan karirmu sebagai seorang designer.
Waktumu juga sering kamu habiskan untuk menemuinya. Lelaki itu, kamu lebih
memilih meluangkan waktumu untuk bertemu dengannya. Bukan denganku.
Mungkin
ada benarnya saat kamu mengatakan bila rasi bintangmu, Gemini dapat
diindeifikasikan dengan sebuah kesetiaan. Kamu begitu setia padanya. Sekalipun
ia pernah mengguratkan luka terdalam padamu. Membuat mata bulatmu seolah redup,
dan tenggelam bersama elegi. Aku tetap mempersilahkanmu menjadikanku sebagai
tempat sandaran pilumu, menjadi pelarianmu. Tapi, rupanya kamu tak menyerah.
Kamu tetap memperjuangkan cintamu yang akhirnya membuat ia mau menikahimu.
Kini,
di sini, aku tengah berdiri di atas karpet merah. Aku berbaris di antara para
tamu undangan. Aku berdiri sendirian. Pasti kamu bertanya-tanya mengapa aku
masih sendiri. Mengapa aku tak bersama Mariska yang sejak kepulangan kita dari
Jogja sering menghubungiku. Aku ingin jujur soal itu. Aku belum siap, Fani. Aku
belum siap untuk mencintai orang lain selainmu. Aku belum siap memenuhi dunia
anganku dengan orang lain selain dirimu. Aku belum siap, Fani. Sudahlah. Lebih
baik kita lupakan dulu tentang aku dan Mariska karena aku sadar aku telah
menyakitinya.
Dari
sini, dari tempatku berdiri, aku bisa melihatmu berdiri berdampingan dengannya.
Tahukah kamu bila saat ini kamu begitu cantik. Kamu menggunakan gaun pernikahan
tercantik yang pernah ada. Kamu berdiri menyambut para tamu undangan dengan
senyum terbaikmu. Senyummu seolah memberikan isyarat padaku bila kamu sudah
bahagia. Dan kamu tahu apa yang kurasakan saat ini? Aku merasakan kebahagiaan
yang sama denganmu, Fani. Terserah bila orang mengatakan aku munafik, tapi
kenyataannya aku memang bahagia. Mungkin rasa cintaku padamu yang berlebih ini
yang membuatku tak dapat berpikir rasional lagi. Tapi, bukankah cinta memang
mengubah manusia menjadi tak rasional?
Kini
giliranku menaiki pelaminan untuk memberikan ucapan selamat padamu. Aku
melangkah dengan perasaan yang tak bisa kuutarakan. Aku sudah siap
melepaskanmu. Esok, tak ‘kan ada lagi sendumu di bahuku. Esok, tak ‘kan ada
lagi tangamu yang melingkar di lenganku. Esok, tak ‘kan ada lagi es krim yang
kita bagi berdua. Esok, tak ‘kan ada lagi kita
karena hanya akan ada, aku. Langkahku sudah semakin dekat dengan kalian. Aku
melangkah menghampiri Bara. Aku tersenyum padanya, menyalaminya, dan
mengucapkan selamat kepadanya. Dan setelah itu aku lantas menghampirimu. Kamu
masih sama seperti kemarin. Kamu masih memberikan senyum termanismu padaku. Aku
pun tersenyum padamu. Aku menatap matamu lekat, ada yang berbinar di sana. Ya,
di matamu. Aku menjabat tanganmu, mengucapkan selamat kepadamu. Tapi, entah
mengapa kamu lekas merengkuhku. Kamu melingkarkan lenganmu di leherku. Ya, kamu
memelukku, Fani. Erat. Pelukan yang begitu erat. Membuatku merasa nyaman berada
dipelukmu. Kamu memelukku erat tanpa mengatakan sepatah kata pun padaku. Hanya
ada aku yang mengatakan selamat padamu. Sesaat kemudian kamu melonggarkan
pelukanmu, dan melepasku. Andai dapat kumiliki pelukmu ini, pastinya tak ‘kan
ku sia-siakan hidupku untuk berada jauh darimu, walau hanya selangkah.
Aku
kembali melangkahkan kakiku menuruni pelaminan. Aku melangkah tanpa sedikitpun
menoleh padamu. Aku tak ingin menoleh padamu karena aku sudah tak ingin lagi
melihat masa laluku. Kini kamu bisa membaca secarik kertas yang sempat
kuberikan padamu saat tadi kamu memelukku. Buka dan bacalah isinya. Sesuai
dengan janjiku untuk menceritakan padamu tentang rasi bintangku dan juga
peranku dalam hidupmu.
Sesuai janjiku, Fani. Inilah mitologi tentang rasi
bintangku, Cancer;
Cancer adalah rasi bintang kecil yang samar-samar. Terletak
di antara Gemini di sebelah barat, dan Leo di timur. Cancer adalah seekor kepiting
peliharaan Hera. Saat Hercules bertarung dengan Hydra, Hera sengaja mengirim
kepiting peliharaannya untuk mengalihkan perhatian Hercules. Hera tak suka
dengan Hercules. Namun, rupanya Hercules terlalu kuat. Capitan Cancer tak
membuat Hercules lemah. Cancer justru mati karena diinjak oleh Hercules.
Kesetiaan Cancer membuat Hera terharu, hingga akhirnya Hera menjadikannya
sebagai sebuah rasi bintang.
Rasi bintang Cancer tak pernah berkelip terang, karena
Cancer gagal dalam menjalankan tugasnya. Sama halnya denganku, Fani. Ya, aku
gagal dalam tugasku. Aku gagal mendapatkan cintamu. Dan lagi, apa kamu masih
ingat bagaimana peran Cancer dalam rasi bintang Gemini? Biar kuingatkan lagi
padamu, Fani.
Gemini terletak di antara Taurus di barat dan Cancer yang
redup di timur. Ya, kamu─Gemini─berada di antara Taurus─Bara─di barat dan Cancer─aku─yang redup di timur. Ya, Fani, aku adalah bintang yang redup
di antara kalian yang bersinar terang. Kini sudah tahukah kamu apa peranku
dalam kehidupanmu? Ya, membuatmu dan dia benderang indah di sana. Itulah
peranku dalam hidupmu.
***





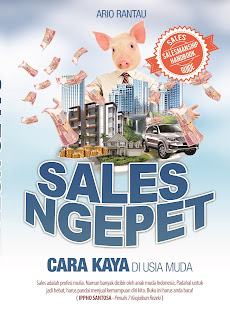








aku ngasih liebster award nih. cek ya http://nirwana-hawra.blogspot.com/2014/08/the-liebster-award-pertama.html
BalasHapusbagus sekali cerpennya ..
BalasHapus