“Sabrina!
Waktunya pulang, sayang!”
Bila aku sudah mendengar kalimat
seperti itu dari Mama, maka aku akan berhenti bermain dan langsung berlari
menghampiri Mama yang sudah menjemputku untuk pulang. Setelah itu Mama akan
menyunggingkan senyumnya sembari merendahkan tubuhnya dan menyambutku dengan
pelukannya. Kemudian Mama akan membalikkan tubuhnya dan membiarkanku untuk
bersandar di punggungnya. Mungkin aku tak seperti anak-anak kebanyakan yang
senang digendong di depan karena aku sangat senang bila Mama menggendongku di
belakang tubuhnya. Membiarkanku berada di punggungnya yang kuat seperti baja.
Bagiku, Mama memiliki punggung yang
kuat seperti baja, namun juga lembut seperti bantal Turki yang terbuat dari
bulu domba. Tak jarang punggung Mama membuatku tertidur saat aku digendong di
atasnya. Selain itu, hal yang paling kusuka dari Mama adalah wangi tubuhnya
yang selalu ingin kuhirup. Mama memiliki wangi tubuh yang lembut dan
menyegarkan, seperti wangi bunga lili
yang pernah kucium saat bertamasya ke taman bunga sebulan yang lalu. Wangi
tubuh Mama selalu mengingatkanku kepada Papa. Tepatnya saat aku bertanya bagian
diri Mama yang mana yang paling disukai oleh Papa. Sambil tersenyum simpul,
Papa pun menjawab dengan suaranya yang terdengar parau, “Wangi tubuh Mamalah
yang paling Papa suka, nak.” Dan kini aku mengerti mengapa Papa begitu menyukai
wangi tubuh Mama yang lembut dan menyegarkan seperti bunga lili ini.
Ah, sial! Aku harus kembali
mengingat soal Papa. Sosok pria yang juga memiliki punggung yang kuat seperti
baja. Pria yang baru saja meninggalkan kami berdua. Walau Papa baru saja pergi
meninggalkan kami, tapi rasanya begitu lama bagiku, membuatku sering
merindukannya. Padahal makamnya saja masih begitu wangi oleh taburan kembang
tujuh rupa. Selain itu tumpukkan tanahnya pun masih berwarna cokelat basah. Benar-benar
mewujudkan sebuah makam yang masih baru. Papa pergi meninggalkan aku dan Mama
karena serangan jantung tepat empat bulan yang lalu.
Masih hangat betul di ingatan ini
bagaimana Mama menangis saat tahu bila Papa tak bisa lagi menemaninya hidup di
dunia ini. Mama terisak dengan begitu sendunya. Bulir-bulir bening terus
berlinang dari matanya, teruntai turun membasuh kulit pipinya yang memerah,
meski tak semerah bola matanya. Tapi saat Mama menyadari kehadiranku, dengan
lekas beliau menyeka linangan air matanya. Saat kutanya mengapa Mama menangis?
Mama hanya memberikan jawaban dengan sebuah senyuman. Saat itu aku belum bisa
mengartikan senyumannya itu. Tapi, kini aku mengerti bila waktu itu adalah senyuman
hampa yang ditunjukkannya untuk menutupi dukanya. Sambil menggelengkan
kepalanya, Mama memelukku seraya mengangkat tubuhku yang kecil ini. Mama
menggendongku. Sepintas terdengar suara seperti sebuah isakkan di telingaku.
Saat itu kuingin tahu apa yang terjadi dengan Mama, tapi eratnya pelukan Mama
membuatku tak bisa bergerak sedikitpun. Aku hanya bisa melingkarkan tanganku di
leher Mama dan menyandarkan kepalaku di pundaknya. Sekali lagi, aku terbius
oleh wangi tubuh Mama.
***
Sejak kepergian Papa, kini Mama
harus berperan sebagai tulang punggung keluarga. Mama harus mencari nafkah
untuk kelanjutan hidup kami berdua. Tapi, Mama hanyalah gadis dari desa yang
hanya bermodalkan ijazah SMA, yang berani datang ke kota untuk menemani suami yang
dipindah tugaskan ke kota sebagai bentuk kenaikan jabatannya di kantor. Tak
banyak skill yang dikuasai oleh Mama,
kecuali skill memasak yang didapatnya
dari orang tuanya terdahulu.
“Buat apa kau melanjutkan sekolah?
Ayahmu itu tuan tanah. Kau hanya perlu hidup dari situ. Jadi, kau tak perlu
melanjutkan sekolahmu dan mulailah membantuku di dapur menyiapkan makan untuk
ayahmu dan calon suamimu kelak.” Begitulah ucapan nenek yang aku tahu dari Mama
yang sering menceritakan itu kepadaku sebagai dongeng sebelum tidur. Alasan
mengapa Mama tak bisa melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi
dan lebih memilih menikah dengan almarhum Papa. Dan terkadang Mama menyesali
keputusan nenek yang melarangnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih
tinggi. Kini tanah warisan kakek hanya tersisa dua. Yang satu dengan luas tak
lebih dari 300 meter persegi yang sengaja ditanami padi untuk kelanjutan hidup
nenek, sedangkan yang satu lagi hanyalah tanah berukuran 2x3 meter di mana
tempat kakek terbaring saat ini. Sesuai dengan permintaan kakek sebelum
meninggal yang ingin jasadnya menyatu dengan tanah hasil jerih payahnya
sendiri.
Sebenarnya hati kecilku tak kuasa
melihat Mama yang bekerja keras untuk menghidupiku. Ingin aku bergerak untuk
membantu Mama mencari nafkah. Tapi apa daya, aku yang masih suka mengenakan
seragam putih-merah ke sekolah ini belum bisa berbuat banyak untuk membantu
Mama. Lagi pula, tiap kali aku ingin bekerja untuk membantu Mama, selalu saja
beliau menjawab, “Tak usah kamu berpikir untuk bekerja, sayang. Sekolah saja
yang pintar. Buatlah perempuan tua ini bangga dengan prestasimu.” Begitulah
yang selalu Mama katakan padaku dengan senyum penuh makna dan pandangan mata
penuh harap yang diperlihatkannya kepadaku. Aku selalu mengangguk seraya
tersenyum setiap kali mendengar ucapan Mama itu. Tapi, setelah itu aku akan
lupa lagi dan kembali mengutarakan niatku kepada Mama untuk bekerja. Aku selalu
ingin bekerja tiap kali aku ingat bila Mama hanyalah seorang pedagang gorengan.
Aku tahu bila Mama begitu lelah dalam
menjalani hidup ini. Air mukanya mengguratkan kelelahan tiap kali pulang ke
rumah saat petang menjelang, apalagi bila masih ada sisa gorengan di dalam
bakul yang terbuat dari anyaman bambu berwarna cokelat pucat yang selalu
digendongnya itu. Napasnya selalu terasa berat dan terengah-engah dengan
keringat yang tak jarang menumpuk di keningnya tiap kali beliau menapakkan
kakinya ke dalam rumah. Tapi semua itu selalu dapat disembunyikannya dengan
senyum yang selalu tersungging di wajahnya tiap kali aku menyambut kepulangannya. Aku selalu suka memijit-mijit pundak Mama di
malam hari setelah aku selesai belajar. Aku tahu bila pijitan dari jemari-jemari
mungilku ini belum cukup untuk memudarkan rasa lelah yang bersandar di pundak
Mama. Aku juga tahu bila Mama telah menanggung banyak beban di pundaknya yang
tampak kecil itu. Tak salah bila pundak itu selalu terlihat menurun tiap
harinya karena terlalu berat menopang beban hidup. Kapan aku bisa membantu Mama
untuk memindahkan beban yang bersandar di pundaknya ini ke pundakku? Batinku
yang selalu bertanya tiap kali jemari-jemari mungilku ini memijit pundak Mama
yang selalu terasa semakin tebal dan kaku setiap harinya.
Perempuan adalah makhluk Tuhan yang
penuh kelembutan yang juga tegar. Begitulah kata para pujangga bila sudah
mendefinisikan tentang perempuan. Tapi ada yang mereka lupa bila perempuan
adalah makhluk Tuhan yang menyimpan kerapuhan juga di dalam dirinya. Aku pernah
terbangun dari tidurku di tengah malam. Saat itu bulan hanya menampakkan
sebagian wujudnya hingga tampak seperti sebuah sabit. Di tengah sadarku yang
hanya setengah, tak sengaja kudengar samar suara seseorang yang tengah terisak
dari balik pintu kamarku. Aku segera bangkit dari tidurku dan beranjak menuju
pintu. Sambil memicingkan mata, dari balik pintu aku mengintip Mama yang tengah
menangis dengan sendunya sambil menaruh sebuah bingkai foto di dadanya. Bingkai
foto yang memampang foto almarhum Papa, dan Mama memeluknya begitu erat. Mama
layaknya Monica Bellucci di film Malena yang tengah rindu dan memeluk erat foto
suaminya yang telah meninggal di medan perang. Tapi bedanya Mama tak
menari-nari dengan foto almarhum Papa. Mama hanya menangisinya.
Sejak
saat itu aku tahu mengapa Mama tak pernah mengeluh di depanku, bahkan Mama tak
pernah sekalipun mengeluh saat tengah memeluk foto almarhum Papa. Mama selalu
mengganti keluhannya dengan linangan air matanya di tengah malam saat aku
tertidur. Mama membiarkan linangan air matanya sebagai pesan yang tersirat kepada
kesunyian malam tentang keluhannya kepada dunia. Dan sejak itu pula aku
mengerti mengapa Mama selalu berpesan kepadaku tentang sebuah ketegaran.
“Janganlah kamu mengeluh, sayang. Perempuan tak boleh
mengeluh.”
“Kenapa, Ma?”
“Karena perempuan adalah makhluk Tuhan yang tegar. Maka
kamu juga harus menjalani hidup ini dengan tegar pula.”
Aku menganggukkan kepalaku walau ku belum begitu mengerti
maksud Mama saat itu. Namun, kini aku mengerti bila Mama ingin aku tumbuh
menjadi perempuan dewasa yang tegar menjalani kehidupan ini, seperti dirinya.
***
Pesan dari Mama itu selalu kuingat
hingga sekarang aku telah menjadi seorang istri sekaligus seorang Ibu layaknya
Mama bagiku. Aku selalu mengajarkan kepada anak perempuanku hal yang Mama ajarkan
kepadaku juga. Dan ajaran itu juga akan diturunkan oleh anakku kepada anaknya, dan
anaknya kepada anaknya lagi, terus dan terus hingga berganti generasi.
Di balik lipatan-lipatan wajahnya yang mulai mempertegas
umurnya, senyum indahnya masih merekah jelas seperti dulu. Bahkan aku masih
sangat senang memeluk Mama dari belakang. Menyandarkan kepalaku di pundaknya
dan membiarkan hidungku menghirup aroma tubuhnya. Aroma tubuhnya memang tak
lagi wangi seperti wangi bunga lili yang lembut dan menyegarkan. Tapi kini
wangi tubuh Mama seperti bau air hujan yang turun di tengah kemarau
berkepanjangan, begitu menyejukkan. Aku selalu senang menghabiskan waktu
seperti ini. Memeluk erat tubuh Mama yang sudah tak semuda dulu dan menghirup
aroma tubuhnya sambil melihat anak-anakku bermain dengan riangnya di teras
rumah. Dan di saat seperti ini hati kecilku selalu berkata, aku akan menjalani
hidup seperti Mama, perempuan paling tegar sekaligus pemilik tulang punggung
baja yang kukenal.
-Sekian-




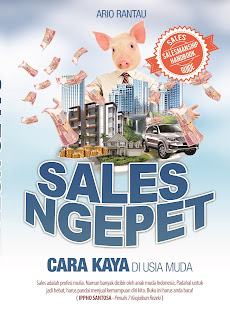








Wah amanat yang terkandung sama persis kayak cerpen biinan temen saya :D Nice !
BalasHapusSalam kenal kawan :) --- Irfan Andriarto ---
Kalau mau ng'blog sambil bisnis Daftar di sini broh, GRATIS ! Lumayan kok di sini Daftar