 |
| (gambar: www.pinterest.com) |
Sementara itu, Rama memutuskan untuk menunggu Sekar di
sisi mobilnya. Berdiri sambil bersandar pada mobilnya. Matanya menatap lurus ke
depan. Tepat ke rumah yang tak terlalu besar dengan pagar teralis yang tingginya
hampir sedadanya. Pintu depannya tersingkap, memancarkan semburat keputihan dari
dalam yang kontras dengan lampu terasnya yang berpendar temaram.
Sepi.
Malam
telah larut dan hanya terdengar lamat-lamat parade para jangkrik yang mengerik.
Semilir angin sempat menerpanya. Menepi ke tengkuk Rama, membuatnya sedikit bergidik.
Tak berselang lama, Sekar pun kembali muncul dari pintu yang terbuka itu. Ia
berjalan menghampiri Rama yang telah menanti kehadirannya.
“Terima kasih ya, Rama. Kau sudah mau menjemput ibuku
lagi,” ujar Sekar begitu berdiri tepat di depan Rama. Sebelah tangannya
menyisihkan sisi rambutnya, yang kemudian diselipkannya ke belakang telinganya.
“Maaf soal tadi. Ibuku masih seperti itu kepadamu,” sambungnya tak enak hati seraya
sedikit menundukkan wajahnya.
“Tak
apa Sekar. Aku mengerti. Dulu kau pun begitu, kan?” sahut Rama tanpa sedikit
pun merasa terhina.
Sekar
tersenyum tipis seraya mengangguk kecil. Ia tak menampiknya bila dulu ia pun
begitu.
Jeda sesaat. Jangkrik-jangkrik masih mengerik.
“Oh, iya. Kau mau masuk dulu? Aku bisa buatkan minum
untukmu.”
“Tidak. Tidak perlu. Sudah terlalu larut. Lebih baik aku
langsung pulang saja.” Rama meraih kunci mobilnya dari saku celananya. Namun,
sesaat kemudian ia terhenti. Ia teringat sesuatu.
“Oh,
iya. Ada sesuatu untuk ibumu.” Rama segera melangkah ke bagasi mobilnya,
membukanya, lalu mengambil sebuah kantung plastik putih yang tampak telah
berisi. Kemudian ia memberikannya kepada Sekar.
“Ini apa?” tanya Sekar begitu menerima kantung plastik
itu dari Rama.
“Di situ ada buah apel dan alpukat. Buah-buah itu baik
untuk jantung. Jadi berikan untuk ibumu. Katakan kepada ibumu untuk sering-seringlah
makan buah-buahan itu.”
“Terima kasih, Rama. Aku tidak tahu harus bagaimana
membalas semua kebaikanmu ini.”
“Tak perlu kau pikirkan soal itu. Anggap saja semua ini
kulakukan sebagai bukti keseriusanku.”
Sekar hanya tersenyum sipu menanggapi ucapan Rama.
Sebelah tangannya menyisihkan sisi rambutnya lagi. Lalu, menyelipkannya ke
belakang telinganya.
Sesaat kemudian Rama pun pamit. Ia melangkah masuk ke mobilnya.
Setelah mesinnya meraung, sedan hitam itu pun lekas melaju membelah pekatnya
malam. Merentas kesunyian di antara temaramnya lampu-lampu jalanan.
Sekar
masih membatu di tepi jalan sambil menjinjing sebuah kantong plastik. Ia masih
di sana sampai mobil itu tak lagi tampak di pelupuk matanya. Menghilang setelah
melewati tikungan.
∞∞∞
Rupanya
perempuan paruh baya itu masih belum juga sudi mengubah penilaiannya terhadap
Rama. Sorot matanya yang penuh benci dan penghakiman itu masih sJ ia tumpahkan
kepada Rama. Sorot mata yang menakutkan. Bahkan hingga hampir satu tahun sudah
Rama berusaha meyakinkan bila ia berbeda, perempuan yang hitam rambutnya telah
sedikit memudar itu tak juga merubah anggapannya.
Rama
tak pernah menyalahkan sorot mata penuh kebencian dan penghakiman yang masih
ditumpahkan itu kepadanya. Sebab dulu Sekar pun memiliki sorot mata yang serupa.
Sorot mata yang memancarkan dendam dan kebencian tatkala ia tahu bila Rama
adalah seorang dokter. Sorot mata yang menakutkan. Rama tahu, pasti ada alasan
dibalik kebencian mereka. Seperti halnya cinta, tentunya kebencian pun perlu
sebuah alasan.
Sesungguhnya,
sorot mata Sekar begitu gelap dan menghunjam. Seolah ada dendam yang telah
mengendap lama di sana. Terkubur bersamaan dengan luka yang masih menganga. Bersemayam
dan siap keluar untuk menerkam setiap kali ia menatap kepada seorang dokter. Tak
terkecuali, Rama. Ya, Rama adalah seorang dokter. Dan setiap kali Sekar
menatapnya seperti itu, maka hanya rasa bersalah yang akan muncul di dalam
dirinya. Rama seolah tengah dihakimi atas perbuatan yang belum pernah
dilakukannya kepada Sekar. Entahlah, mengapa bisa begitu. Tetapi, itulah kekuatan
mata Sekar. Mata yang menyimpan dendam.
“Apa
kau begitu membenci seorang dokter?”
“Ya,”
jawab Sekar dingin seraya terus menggoreskan kuasnya pada permukaan kanvas. Matanya
tak teralihkan sedikit pun dari lukisannya.
Rama
sempat mengalihkan perhatiannya pada lukisan Sekar untuk sesaat. Dilihatnya gambar
seorang Ibu yang tengah menyusui anaknya. Perempuan pada lukisan itu bersanggul
dan mengenakan kebaya tipis seperti perempuan Jawa tempo dulu. Tapi anehnya,
lukisan Sekar tampak kabur dan tak mendetail. Seperti foto yang tak mendapatkan
titik fokus.
“Apa
itu juga berarti kau membenciku?” tanya Rama begitu ia alihkan lagi perhatiannya
kepada Sekar.
“Tidak.
Aku tidak membencimu. Tapi aku membenci profesimu.”
“Memangnya
apa yang salah dengan profesiku? Kenapa kau dan ibumu begitu membenci seorang
dokter?”
Sekar
menghela napasnya. Sejenak ia menghentikan gerakan tangannya. Matanya menatap Rama
untuk sesaat. Kali ini tak ada dendam atau pun kebencian yang tersirat dari
matanya. Entahlah, tapi bisa dibilang bila saat itu sorot matanya tak
menyiratkan apa pun. Kosong. Seperti raga yang sudah tak bernyawa. Sesaat
kemudian ia kembali melemparkan pandangannya pada lukisannya. Menggoreskan lagi
kuasnya.
Rama
sempat lama memerhatikan Sekar. Ia menunggu. Tetapi Sekar tak kunjung berbicara
lagi. Hanya terdengar suara denyit kipas yang berputar di langit-langit meruap
di ruangan ini. Namun, ketika Rama baru akan bertanya sekali lagi, Sekar dengan
sendirinya mulai bicara. Seraya terus menggoreskan kuasnya, ia mulai
menceritakan sebagian sejarah hidupnya.
“Lima
tahun yang lalu, di mana aku masih SMA. Kau pun masih SMA. Kita masih duduk di
kelas dua belas. Saat itu, kondisi ayahku yang tengah menjalani perawatan
pascakecelakaan semakin kritis. Kata dokter, ayahku mengalami epidural hematoma. Semacam pendarahan
pada selaput otaknya dan harus segera dioperasi. Tapi, karena keluargaku tidak
memiliki biaya yang cukup untuk melengkapi administrasi, operasi pun tak
kunjung dilakukan.
Waktu
itu, ibuku sampai membuang rasa malunya untuk memohon dan mengemis kepada
seorang dokter yang akan mengoperasi ayahku. Tapi dokter itu bilang bila ia tak
bisa berbuat apa-apa. Ia tetap tak bisa melakukan operasi karena tak mendapat
ijin dari pihak rumah sakit. Ia terikat dengan peraturan rumah sakit. Ibuku
terus memohon dan menangis. Bahkan ia sampai berlutut di kakinya. Melihat hal
itu tentu membuatku miris. Aku pun ikut memohon dan mengemis kepada dokter itu.
Tapi aku tak sampai berlutut. Hanya ibuku yang rela berlutut kepadanya.
Mengemis dan memohon. Tapi dokter itu malah pergi meninggalkanku dan ibuku.”
Sekar
berhenti sejenak. Ia mengoleskan kuasnya pada paletnya, lalu menggoreskannya
lagi ke permukaan kanvasnya.
“Nyawa
ayahku tak dapat lagi tertolong. Ayahku meninggal hanya karena tak segera
mendapatkan pertolongan yang ia perlukan.” Matanya yang cokelat itu perlahan
mulai menunjukkan jiwanya. Buliran bening pun seketika menggenang di sudut
matanya. Tangannya tak lagi menggiring kuasnya untuk menggoreskan warnanya.
Tapi hanya ia pangku di atas pahanya.
“Bisa
kau bayangkan bagaimana kondisi dan perjuangan ibuku saat itu? Ia berlutut,
mengemis, dan memohon agar suaminya bisa segera dioperasi. Agar suaminya dapat
tertolong. Bahkan ibuku sampai berjanji akan menggadaikan surat tanahnya nanti
untuk membayar biaya operasi. Tapi mereka, para dokter dan pihak rumah sakit
lainnya hanya diam dan seolah tak punya rasa iba. Adakah yang lebih menyakitkan
ketika kau melihat seorang manusia mau mengemis dan memohon kepada orang lain
demi keselamatan orang yang dicintainya?”
Rama
seketika tak dapat bersuara. Bibirnya mendadak kelu untuk sekedar membela
profesinya. Suaranya seolah tersekat di antara merihnya. Bahkan ia tak kuasa
menatap mata Sekar yang kala itu tengah menumpahkan pedihnya. Buliran bening
itu berlinang menelusuri kulit pipi Sekar yang putih. Seperti hujan yang turun
di kala terik. Namun, tak ada pelangi yang muncul sesudah redanya, melainkan
sebuah halimun pekat yang lahir setelahnya. Matanya begitu mendung.
Hanya
dari menceritakan masa lalunya saja sorot mata Sekar sudah begitu berbeda dan
memilukan, antara benci dan sedih, pasrah dan dendam, kehilangan dan kecewa. Semua
itu mampu terlukis pada sorot matanya. Apakah bencinya memang sebegitu kuat
adanya, sehingga bisa mengubah sorot matanya dalam sekejap? Entahlah, batin
Rama termenung.
∞∞∞
Matanya cokelat dan teduh. Rambutnya hitam dan lurus
sebahu. Bibirnya tipis dan selalu tampak alami, sebab ia tak pernah menggunakan
gincu. Wajahnya putih dan cantiknya natural, sebab ia pun tak terlalu suka
berdandan. Selain itu, ia selalu senang mengenakan kaos dan juga flannel yang tak pernah dikancingnya.
Dan ia selalu suka mengenakan celana jeans birun dengan warna yang pudar di
sekitar pahanya. Itulah gadis yang telah setahun belakangan ini selalu menjadi
tempat singgah bagi Rama. Tak peduli meski dulu matanya pernah menatapnya penuh
dendam dan benci. Rama tak pernah letih membuktikan kepadanya jika ia berbeda
dari yang lainnya.
“Apalagi yang kau bawa ini?” tanya Sekar begitu menerima sebuah
kantung plastik putih dari Rama. Ia masih berdiri tepat di pintu pagarnya, menyambut
kedatangan Rama yang mengunjunginya. Padahal baru semalam mereka bertemu. Tapi
sore ini lelaki itu kembali menemuinya.
“Itu isinya irisan ikan tuna dan salmon. Aku baru membelinya
tadi di supermarket. Masakkan itu untuk ibumu.”
“Kau begitu memperhatikan ibuku. Mungkin tak ada salahnya
bila kau menikah dengan ibuku nanti.”
“Bagaimana ibumu bersedia menikahiku bila menjadikanku
menantunya saja ia masih menolak?” seloroh Rama jengkel.
Sekar
mengatupkan rapat mulutnya. Ia menahan kekehnya.
“Apa
ibumu ada di rumah?” tanya Rama seraya menerawangi teras rumah Sekar yang tampak
sepi.
Sekar
menggeleng. “Ibu sedang di salon. Hanya ada adikku di rumah.”
Pantas
bila Sekar begitu sulit untuk diluluhkan bila melihat ibunya yang seperti itu.
Padahal baru semalam Rama menjemputnya dari rumah sakit, tapi itu tak
membuatnya jerah dan berhenti bekerja untuk mengurusi salonnya sendiri. Bila
berkaca pada ibunya, memang tak salah bila Sekar memiliki hati yang tebal juga.
Begitu sulit untuk diruntuhkan. Bahkan, hanya untuk membuatnya mau menarik
kembali kata-katanya merupakan hal yang sangat sukar untuk dilakukan.
Setelah
dirasa cukup basa-basinya, Sekar pun mengajak Rama menuju sebuah rumah kecil
yang tepat berada di samping rumahnya. Tempat Sekar sering menghabiskan
waktunya untuk melukis. Sekar memanglah seorang pelukis. Selepas SMA, ia
putuskan untuk mengambil kuliah seni guna mengasah kemampuannya dalam melukis.
Dan selepas lulus dari kuliahnya, ia pun sering mengikuti pameran-pameran seni
rupa untuk memasarkan lukisannya. Tak jarang pula lukisannya selalu laku
terjual.
Rama
mengambil sebuah bangku plastik warna hijau tanpa sandaran, menaruhnya di dekat
bangku Sekar berada, lalu duduk di atasnya. Dilihatnya sebuah kanvas yang masih
terpasang pada easelnya. Kali ini
Sekar tengah melukis dua anak kecil yang sedang asyik bermain kelereng. Tetapi,
entah di mana mereka bermain, sebab Sekar baru melukiskan wujud dua anak kecil dan
kelereng yang bertebaran di dekat mereka pada kanvasnya.
“Apa
ini lukisan yang akan kau pajang untuk pameran lusa?” tanya Rama begitu Sekar
kembali dari dapur rumahnya untuk menaruh makanan pemberiannya tadi.
“Bukan,”
jawab Sekar begitu mengisi kembali bangkunya. “Lukisanku yang akan dipajang di
pameran itu sudah kusiapkan di sana,” sambungnya sambil menunjuk ke salah satu
sudut ruangan dengan matanya.
Rama
menoleh ke sudut ruangan yang ditunjuk Sekar. Ia mendapati tiga buah lukisan
yang disandarkan pada dinding bercat hijau muda itu. Lukisan-lukisan itu tak jauh
berbeda dengan lukisan Sekar pada umumnya; tak memiliki detail dan agak kabur. Katanya,
lukisannya memiliki unsur impresionisme. Entahlah, apa maksudnya. Apakah itu
berupa aliran atau jenis. Rama tak begitu mengerti.
Sebelumnya
ia pernah menjelaskan hal itu kepada Rama, tetapi Rama sudah lupa dengan
penjelasannya. Yang Rama tahu lukisannya memang menarik. Seperti pada ketiga
lukisannya itu; lukisan tiga perahu nelayan yang sedang bersandar di pinggir
pantai, lukisan seseorang yang tengah meringkuk dan menyendiri di atas
perahunya di tengah danau, dan lukisan seorang penari wanita yang berpakaian wayang.
Semua tak mendetail dan agak kabur. Tetapi tetap saja, begitu menarik untuk
dilihat.
“Apa
hanya tiga itu saja?”
“Ya,
hanya itu. Itu pun aku sudah bersyukur. Aku hampir tak kebagian tempat lagi
karena banyaknya peserta yang mengikuti pameran.”
Saat
itu Rama hanya duduk seraya terus memerhatikan Sekar yang tengah menyelesaikan
lukisannya. Tak ada hal yang lebih menarik baginya selain melihat Sekar seperti
saat ini. Sebab saat melukislah mata Sekar yang cokelat itu akan memancarkan
semburatnya yang berbeda. Tak ada dendam maupun benci. Tak ada kesedihan maupun
kepiluan. Tak ada luka maupun nestapa. Sorot matanya akan tampak begitu teduh.
Membuat siapa pun mau berlama-lama memandangi panorama indah itu. Apalagi seberkas
cahaya tampak menaungi wajahnya tatkala ia tengah konsen menyelesaikan
lukisannya.
Tetapi,
entah mengapa hari ini Rama tak melihat semua itu lagi di wajahnya. Bahkan sinar
wajahnya redup. Seperti bulan yang mengalami gerhana. Sorot matanya membuncah. Seperti
air danau yang tertumpah limbah. Apa yang sedang dipikirkannya?
“Apa
yang sedang kau pikirkan? Wajahmu terlihat begitu cemas.”
“Tidak.
Tidak ada yang kupikirkan. Atau pun aku cemaskan.”
“Ayolah,
jangan menyembunyikan sesuatu dariku. Aku bisa melihat jelas wajahmu menyimpan
kecemasan. Ada apa? Ceritalah,” cecar Rama tak puas dengan jawaban Sekar.
Sekar
tersenyum getir. Ditariknya lagi kuasnya dari kanvas. Ia menghela napasnya amat
dalam, lalu mengembuskannya kembali dengan perlahan. Embusan napasnya terdengar
begitu berat. Sekar seperti sedang memikul beban yang amat berat.
“Aku
memikirkan kondisi ibuku. Aku semakin cemas dengan kondisinya. Dalam sebulan
sudah dua kali ia masuk rumah sakit. Dan yang semalam sudah ketiga kalinya. Aku
takut kondisinya akan semakin memburuk nantinya.”
“Tak
bisakah kau membujuk ibumu agar mau mendapatkan perawatan di rumah sakit?”
Sekar
menggeleng. “Ibuku sudah terlalu benci kepada dokter dan rumah sakit. Bahkan ia
lebih senang mengkonsumsi obat-obatan herbal daripada obat dari dokter. Tapi tetap
saja, bagaimana ibuku bisa sembuh bila ia tak pernah mau memeriksa kondisi
jantungnya ke rumah sakit? Bagaimana ibuku bisa tahu apa yang harus diminumnya
bila ia tak mengetahui jelas tentang penyakit jantung yang dideritanya?” kali
ini suaranya bergetar. Ia berusaha keras mengatur intonasinya. Berusaha untuk
tetap terlihat tegar di depan Rama. Padahal, hatinya sudah cemas tiada tara.
“Andai
aku tak memikirkan ibuku akan hidup menyendiri dan menanggung hidup adikku sendirian,
pastinya aku akan mendonorkan jantungku demi kesehatannya kembali,” sambungnya
lirih seraya menyeka air matanya yang telah menggenang di sudut matanya.
Rama
menatap Sekar penuh simpati. Ia bisa merasakan betapa cemasnya Sekar saat ini.
Ia bisa merasakan sebab ia begitu peduli kepadanya. Siapa yang tak sedih bila
melihat orang yang dikasihinya sedang bersedih?
Jeda
sesaat. Denyit kipas yang berputar di langit-langit masih terdengar meruap.
“Apa
ibuku masih bisa hidup lebih lama lagi?” tanya Sekar sesaat setelah menggoreskan
lagi kuasnya pada permukaan kanvasnya.
Rama
bergeming. Sejujurnya ia bingung harus menjawab apa.
“Katakan
saja, Rama. Bukankah kau seorang dokter? Apalagi saat ini kau sedang
melanjutkan kuliahmu untuk menjadi dokter spesialis jantung.”
“Tapi
aku masih dalam tahap belajar. Aku belum tahu jelas mengenai penyakit ibumu.”
“Kalau
begitu katakanlah sebagai seorang dokter jantung yang masih belajar. Apakah
ibuku akan sembuh dari penyakitnya?” cecar Sekar.
Rama
menghela napasnya panjang. “Ya, Sekar. Ibumu akan hidup lebih lama lagi. Jauh
lebih lama dari yang kau kira,” jawabnya setelah sempat lama berpikir.
Entahlah,
benar atau tidak apa yang dikatakannya. Yang Rama tahu, inilah jawaban
terbaiknya saat ini. Mencoba meyakinkan Sekar bila ia tak ‘kan kehilangan orang
yang dikasihinya dalam waktu dekat ini.
Beberapa
saat berlalu, mereka tak saling berkata-kata. Hanya suara denyitan kipas yang
meruap di sekitar mereka. Sekar masih memakukan pandangannya pada lukisannya
yang sudah hampir selesai. Sorot matanya yang membuncah perlahan telah kembali jernih.
Wajahnya yang redup telah kembali berseri. Sementara Rama senantiasa berada di
sampingnya seraya terus memerhatikannya.
“Rama,
apa kau sadar bila kita ini begitu berbeda dibandingkan SMA dulu?” sahut Sekar
menyingkirkan sepi yang beberapa saat lalu melingkari mereka.
“Ya.
Dulu kita hanya sekedar mengenal muka dan nama saja, tapi tak pernah menghabiskan
waktu bersama.”
Sekar
tersenyum geli. “Lucu ya. Kita justru semakin dekat saat sudah tak satu sekolah
lagi.”
Rama
mengedikkan bahu. “Yaah... terkadang Tuhan memang suka memisahkan dua insan
terlebih dulu sebelum menyatukannya kembali. Anggaplah bila itu adalah cara
kerja Tuhan yang misterius.”
“Ya.
Mungkin,” jawab Sekar seraya menilik lukisannya yang sudah hampir selesai.
Sebelah tangannya menyisihkan sisi rambutnya, yang kemudian diselipkannya ke
belakang telinganya.
Semakin
dekat, ya? Apa ia juga merasakan kedekatan itu, batin Rama.
Rama
memandangi gadis itu dengan rambut hitamnya yang sebahu. Mata cokelatnya yang
teduh. Bibirnya yang tipis dan lebar. Kulitnya yang putih. Dagunya yang mungil
dan meruncing. Sekali lagi, ada yang berdebar di dadanya. Seperti gemuruh
genderang di medan perang. Apakah Sekar dapat merasakan debar ini juga?
“Rama,
apa besok kau ada waktu?”
Rama
terkesiap. “Oh. Iya. Tentu. Ada apa memang?”
“Pameran
itu akan berlangsung lusa. Dan besok malam aku harus sudah meletakkan lukisanku
di sana. Bisa kamu temani aku besok malam untuk menaruh lukisanku di sana? Jika
itu tak merepotkanmu tentunya.”
“Tentu
saja aku bisa,” jawab Rama tanpa berpikir lagi. “Kapan pun akan kusediakan
waktu untukmu.”
∞∞∞
Sedan
hitam itu melaju cepat merentas pekatnya malam. Rama tak terlalu peduli dengan
berbagai kendaraan yang bejalan lambat di depannya. Dengan cekatan ia memacu
mobilnya mendahului kendaraan-kendaraan itu. Entahlah, apakah
kendaraan-kendaraan itu berjalan terlalu lambat, atau Rama yang memacu mobilnya
terlalu cepat?
Di
sampingnya, aura kecemasan masih begitu kentara di wajah Sekar. Ia duduk sambil
terus bersedekap. Bahkan sejak tadi ia tak berhenti menggigit bibir bawahnya
sendiri. Hal itu memang biasa ia lakukan ketika sedang dilanda kecemasan yang
berlebih. Betapa ia tidak cemas? Baru saja selesai memindahkan lukisannya ke
galeri untuk persiapan pameran besok, sebuah kabar buruk langsung
menghampirinya. Adiknya menelepon dan mengatakan bila Ibu mereka tiba-tiba saja
jatuh pingsan sambil memegangi dadanya saat tengah menonton tv. Dan kini ibunya
sedang dilarikan ke rumah sakit dengan sebuah ambulans. Sekar yang mendapati
kabar itu jelas tersekat. Bagaimana pun ia tak mau hal buruk menimpa Ibu yang
amat dicintainya.
Sesampainya
di rumah sakit, tanpa menunggu Rama, Sekar bergegas keluar dari mobil dan
berlari menuju ruang UGD. Setelah melewati pintu kaca yang besar itu, ia mendapati
adiknya tengah duduk sendirian di salah satu kursi yang berarak pada tepian
dinding. Garis mukanya terlihat sedih. Matanya sembap dan air matanya berlinang
deras di pipinya. Dengan lekas Sekar menghampirinya, memeluknya, dan
menenangkannya. Gadis itu berusaha menenangkan adiknya. Padahal dirinya pun
sedang dirundung kecemasan yang tak terkira.
Tak
berselang lama, Rama pun masuk dan berjalan dengan setengah berlari menghampiri
mereka. Ia duduk di sebelah Mawar. Tangannya perlahan menyentuh pundak Mawar
yang selalu bergerak naik-turun beriringan dengan isaknya. Tak banyak yang bisa
dilakukannya saat ini selain berusaha menenangkan Mawar dan juga kakaknya yang
tengah dihujani oleh kecemasan.
Setelah
hampir 45 menit lamanya mereka menunggu, barulah seorang dokter keluar dari
pintu cokelat yang besar itu. Menyadari hal itu, Sekar dengan lekas berdiri. Ia
berjalan dengan setengah berlari menghampiri lelaki yang berpakaian serba putih
itu.
“Bagaimana
kondisi Ibu saya, Dok?” tanya Sekar serta merta. Suaranya bergetar dengan
intonasi yang tak terkendali.
“Anda
ini anaknya?”
“Iya,
saya anaknya! Bagaimana kondisi Ibu saya?”
“Tenang
dulu. Kalau boleh tahu, di mana Ayah Anda?” tanya dokter itu seraya membenarkan
letak kacamatanya yang bulat.
“Ayah
saya sudah meninggal, Dok.”
Dokter
itu diam sejenak. “Kalau begitu mari kita bicara di ruangan saya.”
Walau agak ragu karena Sekar takut untuk
mendengar hal buruk tentang ibunya, tetapi kemudian ia mengangguk juga. Kakinya
mulai melangkah mengikuti jejak sang dokter. Sementara itu, Rama menemani Mawar.
Cukup
lama Rama menunggu hingga Sekar kembali. Bahkan saat ini, Mawar sudah tak lagi
bermandikan air mata. Ia sudah lebih tenang dari sebelumnya.
“Ibu
akan baik-baik saja kan, Kak?” tanya Mawar lirih dan bergetar. Suaranya parau
karena telah habis oleh isakannya tadi.
Rama
menghela napasnya sejenak. Ia tersenyum dan dibelainya lagi kepala Mawar yang
masih tersandar di bahunya. “Ibu kalian pasti akan baik-baik saja. Ibumu adalah
perempuan yang kuat, Mawar,” jawabnya mencoba meyakinkan Mawar.
Inilah
bagian tersulit bagi Rama. Saat ia harus meyakinkan orang lain tentang sesuatu
yang ia sendiri belum yakin dengan hal itu. Tetapi, tugasnya akan lebih berat
lagi ketika ia sudah resmi menjadi seorang dokter spesialis. Sebab saat itulah
ia harus siap bicara apa adanya kepada keluarga pasien. Sekalipun kabar buruk
yang harus disampaikannya. Sesungguhnya, tak ‘kan ada orang yang mau bekerja
hanya untuk menjadi pembawa kabar buruk.
∞∞∞
“Dokter
bilang penyakit jantung Ibu sudah parah. Sudah berada di stadium tiga,” ungkap
Sekar lirih dan bergetar. Matanya sembap karena sendu yang masih enggan
meninggalkannya. Lewat sebuah kaca yang tak terlalu besar, ia menatap nanar
ibunya yang terbaring lemah di ruang ICU. Alat bantu pernapasan terpasang jelas
menutupi hidung dan mulutnya. Di dekatnya, sebuah layar monitor masih terus menggambarkan
garis hijau naik-turun yang tak beraturan.
“Dokter
bilang Ibu mengalami kardiomiopati. Pengerasan
otot jantung yang membuat jantungnya membesar. Dokter mendiagnosa bila umur Ibu
tak ‘kan sampai enam bulan lagi. Bila Ibu ingin sembuh, jalan satu-satunya
adalah lewat transplantasi jantung.” Sekar berhenti sejenak. Ia berusaha
mengatur napasnya. Matanya yang cokelat itu masih basah oleh linangan air
matanya. “Tapi, kata dokter, sangat susah mendapatkan tranplantasi jantung di
sini.”
“Dokter
hanya bisa mengira-ngira, Sekar. Ibumu kuat. Aku yakin itu.”
“Apa
kau bisa menjamin bila yang dikatakan dokter itu tidak benar?”
Rama
seketika membatu. Sekali lagi, ia mencoba meyakinkan orang lain sesuatu hal
yang ia sendiri belum yakin sepenuhnya. Dan kali ini ia gagal. Ia tak bersuara.
Mawar yang tadi membaringkan tubuhnya pada kursi kayu yang tersemat di sisi
dinding telah pulas dalam tidurnya.
“Mungkin
memang baiknya aku mendonorkan jantungku untuk ibuku.”
“Tak
ada orangtua yang tega mengorbankan hidup anaknya. Aku yakin bila kau tanyakan
kepadanya, ia akan lebih memilih mati daripada mengorbankan hidup anaknya.”
“Lalu
aku harus melakukan apa saat ini, Rama? Apa?!” sergah Sekar dengan suara yang
meninggi dan bergetar. Air matanya kembali berlinang. Isaknya kembali pecah.
Dengan lekas Rama mendekapnya. Menenggelamkannya lagi ke dalam peluknya.
“Semua
pasti ada jalan keluarnya Sekar. Pasti ada jalan keluarnya.”
Sekar
terisak dalam dekapan Rama. Terisak dan semakin terisak. Sekar semakin hanyut
dalam kenyataan hidupnya yang pelik ini. Sementara Rama berusaha menenangkan
Sekar lewat dekapannya. Membiarkan linangan air matanya membanjiri polo shirt biru dongker yang dikenakannya.
Menjadikan pundaknya sebagai sandaran pelipur laranya. Baginya tak mengapa,
asalkan pilu gadis yang dikasihinya ini dapat segera sirna.
∞∞∞




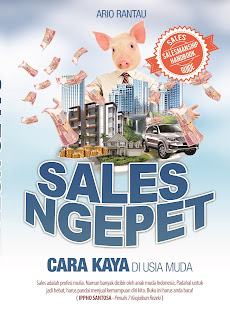








ada part 1 pasti ada part 2 nya kan :)
BalasHapusTunggu seminggu lagi ya :)
HapusBagus kak cerpennya, ditunggu berikutnya :)
BalasHapusRama :* nice!
BalasHapuscewealpukat.me